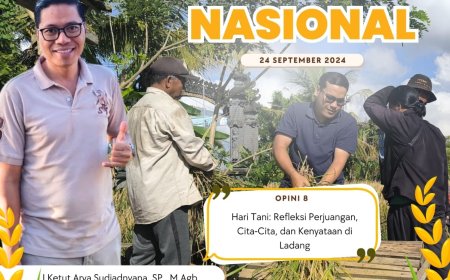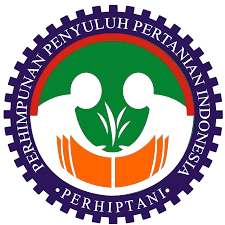“Petani Bisa Jual Karbon, Bukan Hanya Gabah”
Bagi petani, ini bukan sekadar tambahan pendapatan. Petani tidak hanya panen gabah, tetapi juga panen karbon. Perhiptani, sebagai organisasi profesi yang memiliki jejaring luas, berfungsi memfasilitasi koordinasi antara petani, pembeli karbon, dan pihak-pihak terkait sehingga transaksi menjadi transparan dan saling menguntungkan.

“Petani Bisa Jual Karbon, Bukan Hanya Gabah”
Suasana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Banjarangkan siang itu berbeda dari biasanya. Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas koordinator dan penyuluh pertanian dari empat kabupaten Klungkung, Karangasem, Gianyar, dan Bangli berkumpul dalam Focus Group Discussion (FGD) gelombang kedua, Jumat (12/9).
FGD tersebut mengusung tema “Implementasi Teknologi Irigasi Berselang dan Perdagangan Karbon pada Budidaya Padi Sawah.” Para peserta tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menatap masa depan pertanian yang lebih ramah lingkungan dengan nilai tambah ekonomi dari program kredit karbon.

Sawah Jadi Sumber Cuan Baru
Karbon dinilai menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan iklim. Program ini memungkinkan petani memperoleh penghasilan tambahan jika menerapkan praktik budidaya berkelanjutan, misalnya melalui irigasi berselang atau irigasi tetes. Cara ini terbukti mampu mengurangi emisi metana, salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global.
“Program ini masih tahap awal, tapi potensinya besar. Jika banyak petani terlibat, kita bisa berkontribusi nyata pada penanganan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Prof. J. Stephen Lansing, peneliti dari Nanyang Technological University Singapore, yang hadir sebagai pembicara utama.
Hal senada disampaikan Dr. Ir. I Wayan Alit Artha Wiguna, M.Si. Ia menekankan bahwa irigasi berselang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga bisa meningkatkan hasil panen sekaligus menekan biaya produksi.

Dr. Alit menuturkan, sawah tidak lagi hanya bicara soal gabah. Dengan penerapan irigasi berselang, lahan subak kini mampu memberi sumbangan besar pada bumi. Mengurangi emisi metana yang setara dengan 33 ton karbon per hektare dalam setahun.
Jika harga kredit karbon di pasar internasional dipatok 10 dolar AS per ton, maka setiap hektare sawah berpotensi menghasilkan:
33 ton x USD 10 = USD 330 per tahun
(≈ Rp5 juta, dengan kurs Rp15.000/USD)
Bayangkan bila satu subak dengan 100 hektare lahan ikut serta:
100 hektare x USD 330 = USD 33.000 per tahun
(≈ Rp495 juta)
Atau jika skala diperluas ke ribuan hektare di Bali, nilainya bisa menembus miliaran rupiah setiap tahun.
Bagi petani, ini bukan sekadar tambahan pendapatan. Kredit karbon membuka peluang baru. Sawah mereka bukan hanya penghasil pangan, tapi juga penjaga iklim global.
“Dengan demikian, petani tidak hanya panen gabah, tetapi juga panen karbon. Subak pun berpeluang menjadi lembaga ekonomi baru yang mengelola dana karbon untuk kesejahteraan anggotanya,” tandasnya.
Penyuluh dari berbagai daerah menilai program ini layak disosialisasikan lebih luas agar para petani mau beralih ke pola tanam berkelanjutan. Dalam upaya mengoptimalkan potensi sawah sebagai penyerap karbon, proses jual beli karbon tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah peran Perhiptani dan penyuluh pertanian menjadi sangat krusial.
Perhiptani, sebagai organisasi profesi yang memiliki jejaring luas, berfungsi memfasilitasi koordinasi antara petani, pembeli karbon, dan pihak-pihak terkait sehingga transaksi menjadi transparan dan saling menguntungkan. “Kita harus menjadi jembatan pengetahuan bagi petani di lapangan,” kata Ketua Harian DPW Perhiptani Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, S.P., M.Agb didaulat sebagai moderator.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang diskusi.
Diskusi semakin hidup saat sesi tanya jawab dibuka. Para penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten di Bali melontarkan pertanyaan kritis terkait peluang, tantangan, hingga teknis implementasi program kredit karbon di lahan sawah.
Pertanyaan pertama datang dari Penyuluh Pertanian Kabupaten Klungkung, Desak Made Diah Wijayanti, SP, M.Agb. Ia menanyakan sejauh mana peran subak diperlukan dalam penerapan program ini, mengingat pengelolaan lahan subak berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan selain hasil panen padi.
Dr. Alit menjawab dengan lugas, bahwa peluang ekonomi subak kini tidak hanya berasal dari panen padi, melainkan juga dari pengelolaan emisi gas metana. Pasar karbon global sudah menjadi mekanisme resmi yang memberikan insentif finansial. Dengan persetujuan subak sebagai lembaga tradisional pengatur tata air dan pertanian, pengurangan emisi metana bisa dijalankan. Petani akan memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon, sekaligus menjaga ekosistem sawah. Bahkan, hal ini dapat dipadukan dengan agrowisata yang mengedukasi wisatawan tentang pertanian berkelanjutan.

Penanya kedua diajukan oleh Koordinator BPP Selat Karangasem, I Made Suryadi, SP. Dengan gaya jenaka, ia mempertanyakan bentuk produk yang dipasarkan dalam skema kredit karbon. “Apakah berupa alat teknologi, data pengukuran, atau karbonnya dibungkus plastik seperti jual es lilin?”
Kedua Narasumber sembari tersenyum menjelaskan, bahwa produk utama bukanlah barang fisik, melainkan nilai ekonomi dari gas metana yang berhasil dikurangi atau ditangkap. Melalui praktik irigasi intermiten dan pengelolaan lahan, hasil pengurangan emisi itulah yang kemudian diperdagangkan di pasar karbon.

Tak ketinggalan pula pertanyaan datang dari Penyuluh BPP Banjarangkan, NBG Suryadarma, TR, S.P. Ia mengungkapkan kekhawatiran terkait tantangan teknis di lapangan, seperti intermitensi pengairan, keraguan petani, serta cepatnya pertumbuhan gulma. Ia menanyakan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut sekaligus cara terbaik meyakinkan petani.
Dr. Alit pun dengan tegas menekankan, bahwa kunci utama ada pada kapasitas penyuluh. Dengan benar-benar menguasai teknologi dan materi yang dipaparkan, penyuluh dapat meyakinkan petani akan manfaat jangka panjang sistem ini.
Berondongan pertanyaan pun datang dari kandidat jawara penyuluh pertanian berprestasi asal Kabupaten Gianyar, Ni Kadek Sintya Dewi, S.P. Ia menyoroti dua hal. Pertama, peran teknis penyuluh dalam mendampingi petani pada program perdagangan karbon. Kedua, mengenai penggunaan ordok/gasrok dalam sistem irigasi intermiten. Ia bertanya apakah alat tersebut bisa dimodifikasi dengan mesin pemotong rumput agar lebih efisien dan menarik minat petani. Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana cara memperoleh dukungan berupa alat pengukur gas metana untuk implementasi di subak.
Kedua narasumber menegaskan, bahwa peran penyuluh sangat penting sebagai pendamping teknis petani dalam skema perdagangan karbon. Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, akan disediakan alat pengukur gas metana sehingga implementasi bisa berjalan nyata di subak. Terkait modifikasi ordok, ide pengembangan tersebut dinilai sangat memungkinkan agar penggunaannya lebih efektif dan ramah bagi petani.
FGD diakhiri dengan komitmen bersama untuk mendorong implementasi teknologi ramah lingkungan tersebut. Harapannya, pertanian padi di Bali tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mampu memberi manfaat ekonomi baru melalui perdagangan karbon.
Kontributor DPD Perhiptani Kabupaten Klungkung

What's Your Reaction?
 Like
1
Like
1
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0