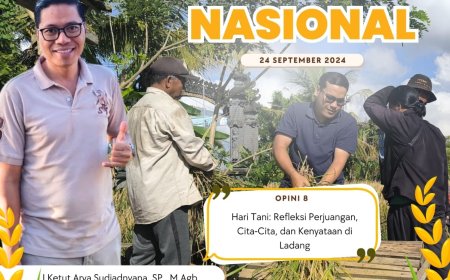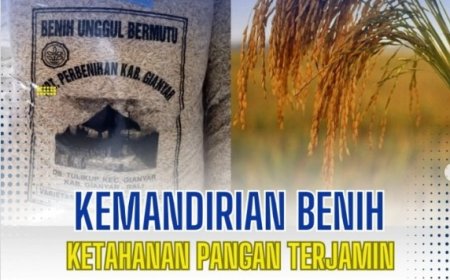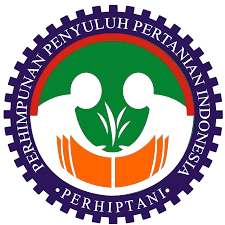Rasionalisasi WKPP di Tengah Tantangan Pangan Bali
Perpindahan status penyuluh pertanian dari ASN daerah ke ASN pusat membawa banyak cerita. Di atas kertas, ini tampak sebagai langkah maju. Tapi di lapangan, perpindahan ini tak sekadar soal administrasi. Di tengah kekurangan hampir tiga ratus tenaga penyuluh, pertanyaan besarnya sederhana, apakah idealisme “satu desa, satu penyuluh” masih bisa diwujudkan?

Ketika Penyuluh Harus Berpindah (1)
Rasionalisasi WKPP di Tengah Tantangan Pangan Bali
Ada yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan penyuluh pertanian Bali belakangan ini. Bukan soal harga pupuk yang naik-turun seperti suhu politik menjelang pilkada, bukan pula soal cuaca ekstrem yang membuat petani lebih sering menatap langit dari hamparan padi.
Kali ini, yang ramai dibicarakan adalah “pindah rumah besar-besaran” mempertahankan status penyuluh pertanian dari ASN daerah menjadi ASN pusat di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Sekilas, ini tampak seperti kabar baik. Akhirnya, para penyuluh benar-benar “pulang” ke rumah induk Kementerian Pertanian. Namun, di balik rasa bangga itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Bali siap memenuhi idealisme satu desa satu penyuluh?
Jawabannya, sayangnya, belum.

Realita di Lapangan: 636 Desa, 80 Kelurahan, dan 430 Penyuluh
Data sederhana ini sudah cukup bicara. Bali memiliki 636 desa dan 80 kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian aktif hanya sekitar 430 orang. Kalau saja penyuluh bisa dibelah dua seperti batang batang singkong, mungkin masalahnya selesai. Tapi tentu saja tidak ada lagi yang seperti itu.
Dengan prinsip ideal “satu desa, satu penyuluh”, Bali masih kekurangan hampir 300 orang tenaga penyuluh. Itu bukan angka kecil. Di balik setiap menampilkan satu posisi penyuluh, ada satu desa tanpa pendamping tetap, satu kelompok tani tanpa teman berdiskusi, dan mungkin satu lahan yang tak menyentuh inovasi.
Oleh karena itu, rasionalisasi wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) menjadi langkah yang tak terelakkan. Suka tidak suka, pengaturan ulang wilayah kerja harus dilakukan. Dan disitulah dilema bermula.
Kementerian Pertanian punya target mulia. Meningkatkan produksi pangan nasional dan memperkuat kemandirian beras di tengah ancaman perubahan iklim dan gejolak harga global. Namun di lapangan, para penyuluh adalah ujung tombak yang memastikan semuanya tak berhenti di atas kertas.
Mereka menemani petani dari awal tanam hingga panen, dari menyiapkan lahan hingga menghadapi gagal panen. Tapi dengan satu penyuluh yang harus membina dua, tiga, bahkan empat desa, bagaimana mungkin pendampingan bisa berjalan ideal?
Seorang penyuluh di Tabanan sempat berkelakar, “Sekarang saya lebih hafal jadwal pompa air subak daripada jam makan sendiri.
” Sementara yang lain menambahkan, “Kalau motor dinas kami bisa bicara, mungkin sudah minta cuti.”
Humor itu memang ringan, tapi di baliknya tersimpan beban kerja yang nyata.

Saat Sawah Tak Seimbang dengan Jumlah Penyuluh
Data dari ATR/BPN menunjukkan ketimpangan antara luas baku sawah dan jumlah penyuluh di setiap kabupaten. Tabanan, misalnya, dikenal sebagai “lumbung padi Bali” dengan lahan terluas. Ironisnya, justru di sanalah jumlah penyuluh paling sedikit. Ada wilayah kerja yang begitu luas hingga penyuluh berseloroh, “Kalau mau kunjungan lapang, harus isi bensin dua kali.”
Gianyar pun menghadapi situasi serupa. Meski memiliki subak-subak produktif yang terkenal dunia, jumlah penyuluhnya masih jauh dari ideal. Satu penyuluh bisa membina lebih dari lima subak aktif sekaligus.
Sementara itu, kabupaten seperti Klungkung atau Bangli, memiliki lahan sawah yang lebih sempit, relatif lebih seimbang antara luas lahan dan jumlah penyuluhnya.
Ketimpangan ini membuat rasionalisasi WKPP tak bisa ditawar. Bukan sekadar soal memindahkan orang, tetapi soal memastikan setiap hektar sawah dan setiap kelompok tani tidak berjalan sendirian.
Proses yang Tak Sekadar Pindah Tugas
Bagi banyak penyuluh, wilayah kerja bukan sekadar lokasi administratif. Itu adalah tempat mereka tumbuh bersama petani, tempat mereka belajar bahwa penyuluhan bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga mendengar, memahami, dan memotivasi.
Ketika kebijakan rasionalisasi mengharuskan mereka pindah antar kecamatan, bahkan antar kabupaten, ada rasa seperti “pindah rumah kedua”. Ada nostalgia terhadap kelompok tani yang sudah dianggap keluarga. Namun di sisi lain, muncul juga semangat baru wilayah baru, tantangan baru, peluang baru.

Seorang penyuluh bergurau, “Kalau dulu saya hafal semua nama ketua kelompok tani di kecamatan saya, sekarang saya hafal semua sopir truk pengangkut gabah.”
Di balik tawa itu, ada ketulusan dan keteguhan untuk tetap mengabdi. (Bersambung)
What's Your Reaction?
 Like
4
Like
4
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0